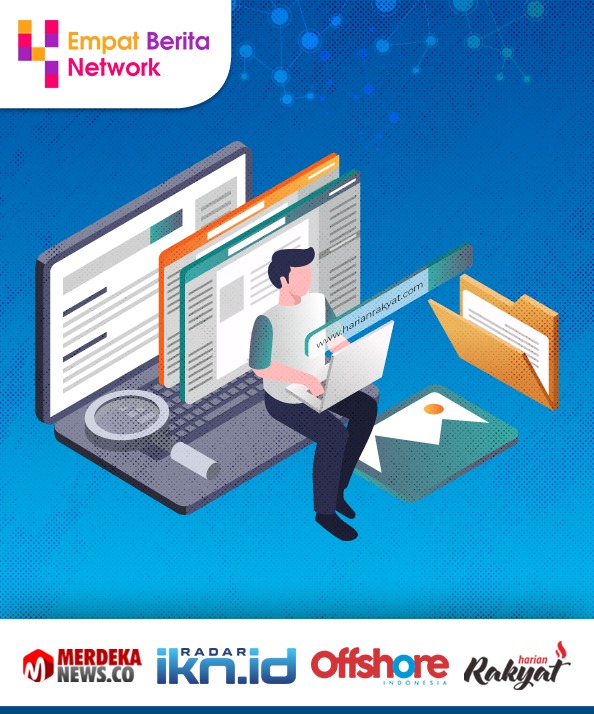Jakarta, MERDEKANEWS - Politik identitas kembali mengemuka belakangan ini. Dan, Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) DKI disebut salah satu yang merangsang lahirnya wacana ini.
Kemunculannya politik identitas di Pilkada DKI, difasilitasi kontestasi petarungan politik. Lalu, bagaimana dengan daerah lain? Dalam studi paska kolonial, politik identitas sudah lama digeluti dan ditekuni. Para pemikir politik identitas seperti Ania Loomba, Homi K Bhabha, dan Gayatri C Spivak.
Mereka kerap menjadi rujukan lantaran meletakkan politik identitas sebagai ciptaan dalam wacana sejarah dan budaya. Berdasarkan literatur ilmu politik, politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik (political identity) dengan politik identitas (political of identity).
Di mana, identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas politik. Sedangkan politik identitas mengacu pada mekanisme pengorganisasian identitas.
Baik dalam identitas (politik identitas maupun sosial identitas sebagai sumber dan sarana politik).
Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam petarungan merebut kekuasaan politik, sangat dimungkinkan dan kian mengemuka. Karena itu, para ilmuwan yang bergelut dalam wacana politik identitas, berusaha sekuat mungkin untuk menafsirkan kembali dengan logika sederhana dan lebih operasional.
Misalnya, Agnes Heller mendefinsikan, politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Sedangkan, pakar politik dari Universitas Duke, Donald L Morowitz (1999), mendefinisikan politik identitas adalah pemberian garis tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak.
Karena garis-garis penentuan tersebut tampat tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota dan bukan anggota akan bersifat permanen. Baik Agnes Heller dan Donald L Morowitz memerlihatkan sebuah benang merah dari politik identitas yang dimaknai sebagai politik perbedaan.
Kemala Chandakirana (1999) dalam artikelnya Geertz dan Masalah Kesukuan mengatakan, politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai sebuah retorika politik. Seperti dengan sebutan “Kami orang asli”.
Kalimat ini memberi pesan bahwa mereka tengah menghendaki kekuasaan. Sebaliknya, sebutan “orang pendatang”, ini ditujukan untuk melepaskan kekuasaan. Singkatnya, politik identitas sekadar dijadikan alat untuk memanipulasi dan menggalang politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya (Muhtar Haboddin: 2012).
Suparlan memaknai politik identitas harus dilekatkan pada konsep identitas itu sendiri atau disebut juga sebagai jati diri. Menurutnya, identitas atau jati diri adalah pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang dikaitkan dilekatkannya rangkaian ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang menandainya masuk dalam satu kelompok atau golongan tertentu (Parsudi Suparlan, 2004: 25).
Widayanti (2009: 14-15), ada tiga (3) pendekatan pembentukan identitas. Pertama, primodialisme. Identitas diperoleh secara alamiah, turun temurun. Kedua, konstruktivisme. Identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat. Ketiga, instrumentalisme. Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan.
Cressida Heyes dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy, mendefinisikan, politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas, dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu.
Buchari dengan mengutip Jumadi (2009), mengemukakan, konsep identitas secara umum dapat dimaknai sebagai sebuah citra yang membedakan individu atau suatu kelompok dengan individu atau kelompok lain.
Hal tersebut dilakukan secara simultan dalam interaksi sosial sampai memunculkan opini tertentu yang berkaitan dengan keberadaan individu atau kelompok tersebut (Sri Astuti Buchari, 2014: 27).
Kata Castells, identitas merupakan atribut yang melekat kepada seseorang secara kultural. Masyarakat Tionghoa di Indonesia secara tegas teridentifikasi sebagai kelompok masyarakat non pribumi yang terpisah dari masyarakat asli Indonesia walaupun dalam diri mereka melekat identitas kesukuan Indonesia seperti Jawa (Cina jawa), Batak (Cina Batak), Manado (Cina manado), Betawi (Cina Benteng), dan lain lain.
Identifikasi tersebut tidak hanya diberikan oleh orang di luar Tionghoa, tetapi dilekatkan pula oleh komunitas mereka sendiri berdasarkan struktur silsilah etnis mereka secara genetik dan budaya nenek moyang.
Merujuk pada beberapa pemahaman di atas, politik identitas berakar pada streotif yang dilekatkan dengan menggunakan perspektif primordialisme. Mengikuti konsep polity Aristoteles, primordialisme berarti “berperang ke luar dan konsolidasi ke dalam”.
Karena itu, politik identitas selalu diwarnai konflik baik yang bersifat frontal maupun yang dialektik. Politik identitas selalu ada dalam wilayah ketegangan antara superioritas dan inferioritas. Antara mayoritas dan minoritas (Suryani dan Ana Sabhana Azmy, 2016: 29-30).
Pintu Masuk dan Pemilu
Menguatnya politik identitas di ranah lokal bersamaan dengan dimulainya dengan politik desentraliasi. Adalah disahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai alasannya. Sebagian isi UU tersebut, Pasal 56 hingga 119 bermuatan materi tentang prosedur dan mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seacara langsung oleh rakyat.
Kehadiran UU tersebut, menjadi pintu masuk aspirasi daerah yaitu keinginan untuk memiliki pemimpin lokal yang disepakati oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.
Dalam bingkai pemilihan umum (pemilu), identitas bukan hanya persoalan primodialisme semata. Akan tetapi belakangan ini, identitas bertransformasi sebagai alat politik dalam menarik simpati publik atau malah sebaliknya (LSN dan FFH, 2014).
Lazimnya digunakan digunakan pada rejim pemilu seperti pilkada. Hal ini dikarenakan daerah operasional pilkada yang sifatnya lokal. Akibatnya, banyaknya kandidat yang mengusung tema etnis dengan dalih mewakili kelompok tertentu.
Contoh, studi kasus Cornelis Lay-Cristiandy Sanjaya di Pilkada Kalimantan Barat 2007. Keduanya malah mampu mengemas dan mengkapitalisasi soal politik identitas yang menimpa mereka selama kontestasi.
Studi kasus Pilkada Kalimatan Selatan 2010. Kekalahan Zaerullah Azzar-Aboe Bakar Al Habsyi disebabkan sentimen kesukuan. Zaerullah terkena isu bukan Banua alias bukan asli Kalimatan. Peredaran isu itu terjadi di ruang tertutup. Seperti melalui pesan berantai (sms). Tidak berada di ruang terbuka seperti di media massa atau sosial media seperti Facebook, dan lainnnya. Walhasil, potensi ledakan tidak terlihat dengan mata telanjang
Kontras sekali dengan Pilkada DKI 2017. Pembahasan dan perdebatan politik identitas berada dalam ruang terbuka. Bahkan frekuensi cenderung meningkat pada masa kontestasi. Media massa seperti media cetak, tv, dan online serta dan sosial media seperti Facebook seperti menjadi amplifier dan memproduksi isu politik identitas. Isu politik identitas pada Pilkada DKI menerpa Basuki Tjahaya Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
Di Pilkada Kota Solo 2015, saat pencalonan FX Hadi Rudyatmo yang beragama Katolik dan Pilkada Kabupaten Banjarnegara 2017 dengan calon Budhi Sarwono alias Wing Chin dengan latar belakang etnis Tionghoa.
Akan tetapi, penggunaan isu SARA di kedua daerah tersebut tidak menimbulkan efek besar. Keduanya tetap terpilih sebagai pemenang. Selain itu, media tidak memberitakan secara luas dan masif pertarungan politik di Solo dan Banjarnegara.
Pilkada Gelombang III
Tahun 2018 sering disebut dengan tahun politik. Hal ini disebabkan berhimpitan dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden 2019. Makna 2018 sebagai tahun politik semakin berbobot lantaran ada 171 wilayah yang melaksanakan pilkada. Dengan rincian, 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Salah satu provinsi yang termasuk 17 itu yakni Jawa Barat.
Dalam kacamata elektoral, Jawa Barat adalah provinsi tergemuk soal urusan jumlah pemilih. Makanya tidak heran apabila semua partai politik pasang target tinggi di Pilkada Jawa Barat. Ada empat (4) calon yang betarung di Pilkada Jawa Barat. Mereka adalah Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, dan TB Hasanuddin-Anton Charliyan.
Pemilihan masing-masing pasangan calon di atas tentu saja sudah dipikir dan dihitung dalam ranah matematika pilkada partai politik. Seperti representasi wilayah, profesi pekerjaan, gender, dan lainnya. Argumentasi itu kemudian diterjemahkan ke dalam definisi operasional pemenangan. Dalam bentuk teknisnya seperti tagline atau slogan yang dinarasikan ke dalam berbagai bentuk. Seperti Nyunda, Nyantri, Nyakola, dan lainnya. Narasi itu diproduksi ke dalam berbagai bentuk alat peraga kampanye (APK) seperti baliho, spanduk, poster, dan lainnya.
Dalam sejumlah literature dikatakan Jawa Barat termasuk dalam kategori provinsi homogen. Hal ini dilatarbelakangi dengan komposisi suku Sunda berada dalam kisaran 70-80 persenan. Jika menggunakan pendekatan demograpi maka argumen Jawa Barat adalah provinsi homogen dapat dibenarkan.
Pertanyaannya, apakah para calon hanya bergantung pada strategi pemenangan memanfaatkan angka 70-80 persen itu? Atau petarungan menggunakan strategi gagasan dan ide untuk Jawa Barat pada masa akan datang?
Dalam riset Founding Fathers House (FFH) dan Surabaya Survey Center (SSC) akhir tahun lalu, mayoritas publik tidak setuju bahwa politik berbau suku, agama, rasa, dan antar golongan (SARA) dijadikan sebagai satu-satunya metode pemenangan dalam kontestasi pilkada.
Sebaliknya, mayoritas publik setuju bahwa perbedaan suku, agama, rasa, dan antar golongan (SARA) dijadikan kekayaan keragaman. Namun, masyarakat terbelah menjadi dua (2) bagian soal tingkat khawatiran residu atau sisa-sisa petarungan politik identitas di Pilkada DKI tidak menular di wilayah mereka. Ada yang menilai khawatir dan ada yang tidak khawatir.
Penulis: Dian Permata
Peneliti Senior Founding Fathers House (FFH)
(Setyaki Purnomo)